Setelah disahkannya undang-undang guru dan dosen, yakni Undang-Undang No.14 Tahun 2005, profesi guru dan dosen kembali menjadi perhatian dikalangan banyak pihak, baik yang berkecimpung dalam dunia pendidikan maupun dikalangan pemerhati pendidikan. Mengapa tidak, kehadiran undang-undang tersebut telah menambah wacana baru akan dimantapkannya hak-hak dan kewajiban bagi guru dan dosen. Di antara hak yang paling ditunggu-tunggu selama ini adalah adanya upaya perbaikan kesejahteraan bagi guru dan dosen. Sayangnya, kehadiran undang-undang ini menemui banyak kendala dalam implementasinya, bahkan rektor UGM (Sofian Effendi) pernah mengatakan bahwa undang-undang guru dan dosen hanyalah sebuah pepesan kosong kalau urgensi dan subtansinya tidak realistis diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan (gaji) guru dan dosen.
Disamping itu, adanya beberapa pasal yang belum jelas bentuk implementasinya, khususnya pasal yang mengatur kualifikasi pendidikan dan pemberian tunjangan profesi. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik (untuk dosen diatur dalam Pasal 45). Sertifikat pendidik ini merupakan prasyarat untuk memperoleh tunjangan profesi dan pengakuan sebagai tenaga profesional. Kemudian dalam Pasal 16 disebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Dengan demikian seorang guru atau dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik, akan mempdapatkan penghasilan yang terdiri dari : (1) gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, (2) tunjangan fungsional, dan (3) tunjangan profesi. Disamping itu, guru dan dosen akan menerima tambahan penghasilan lain dalam bentuk tunjangan khusus bagi mereka yang bertugas di daerah khusus.
Kalau dikalkulasi, penghasilan guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik memang memberikan harapan kesejahteraan yang sudah cukup. Tetapi kemudian masalahnya adalah harapan ini nampaknya masih dalam bentuk fatamorgana, karena untuk memperoleh tunjangan profesi yang diidamkan itu, harus melalui proses yang panjang. Dengan kata lain guru harus menunggu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mengapa tidak, kalau dilihat dari persyaratan yang diajukan bahwa untuk memperoleh tunjangan profesi seorang guru harus mempunyai kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya diploma empat (D4) dan harus mengikuti pendidikan profesi agar memperoleh sertifikat pendidik. Sementara itu, data dari kepegawaian (BAKN) menunjukkan bahwa ada ratusan ribu atau lebih guru-guru kita yang masih mempunyai kualifikasi pendidikan di bawah diploma empat (SLTA, SPG, PGSLTP, D1, D2, dan D3).
Dengan demikian bisa dibayangkan kalau sekiranya harus menunggu para guru yang belum memenuhi kualifikasi itu memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk implementasi undang-undang guru dan dosen. Apalagi kalau biaya untuk penyelenggaraan peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru itu diharapkan dari dana APBN atau APBD yang jumlahnya sangat terbatas. Berdasarkan hal tersebut, suatu pertanyaan diajukan adalah : apakah sertifikasi guru dan dosen itu suatu harapan yang bisa diwujudkan guna mendapatkan imbalan finansial (gaji) yang layak bagi guru dan dosen ataukah sebuah bentuk pelecehan terhadap profesi guru dan dosen maupun terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ? Pertanyaan ini perlu diajukan karena paling tidak ada dua hal yang perlu dikaji berkaitan dengan pemberian tunjangan profesi.
Pertama, seorang guru atau dosen digaji berdasarkan jasanya atau sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Jadi kalau ada upaya pemerintah untuk menaikkan gaji guru dan dosen dalam bentuk pemberian tunjangan profesi, maka tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja guru dan dosen. Sama halnya alasan yang dikemukakan oleh pemerintah ketika akan menaikkan gaji pejabat atau anggota dewan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja pejabat atau anggota dewan serta untuk menghindari adanya praktek penyalahgunaan wewenang dalam bentuk KKN (kolusi, korupsi, nepotisme). Sehingga untuk menaikkan gaji pejabat dan anggota dewan tidak perlu ada persyaratan khusus seperti harus mempunyai sertifikat tertentu. Sekedar perbandingan, bahwa gaji seorang anggota dewan pada tingkat pusat (DPR RI) untuk satu bulan bisa dipakai untuk membayar gaji guru sebanyak 30 orang.
Oleh karena itu, adalah sangat tidak pantas apabila pemberian tunjangan profesi kepada guru dan dosen disertai persyaratan harus punya sertifikat pendidik Program sertifikasi itu lebih tepat ditujukan kepada mereka yang masih berstatus calon guru ataukah guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan yakni minimal diploma empat Hal ini didukung dalam Pasal 12 yang berbunyi : setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Pasal 12 ini sebenarnya telah mengindikasikan bahwa sertifikat pendidik itu sebaiknya diberikan kepada calon guru, bukan kepada orang yang sudah menjadi guru.
Kedua, LPTK adalah lembaga yang mendidik calon-calon tenaga guru. LPTK ini kemudian mengeluarkan dua sertifikat, yaitu Ijazah dan Akta (untuk program S1 berupa ijazah sarjana dan akta IV). Dengan demikian, kalau seorang guru atau dosen yang telah memiliki ijazah sarjana (S1) dan Akta IV apalagi dia adalah alumni dari suatu LPTK, kemudian kepadanya diharuskan lagi memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi, apakah ini bukan suatu bentuk pelecehan baik terhadap guru dan dosen ataupun terhadap LTPK itu sendiri. Sehingga, kalau hal ini tetap dilakukan berarti sertifikat pendidik itu lebih tinggi kualitasnya/nilainya daripada ijazah Akta IV. Kalau demikian halnya untuk apa ijazah akta itu dikeluarkan oleh LPTK ? Bukankah LPTK itu sebenarnya adalah suatu lembaga profesi yang tujuan utamanya adalah mendidik calon-calon guru ? Bandingkan di luar negeri yang tidak mengenal LPTK (IKIP/FKIP). Apalagi kalau pendidikan profesi itu nantinya hanya diikuti oleh guru dan dosen dalam waktu singkat, misalnya paling lama satu bulan. Kemudian mereka diuji/diberikan tes dalam bentuk soal-soal pilihan ganda atau hanya mengukur aspek kognitif yang sifatnya instan (sesaat) lalu keluar keputusan bahwa kepadanya dinyatakan lulus dan diberi sertifikat pendidik. Kalau pelaksanaannya demikian, berati program sertifikasi itu lebih kental nuansa proyeknya dari pada urgensi dan subtansinya. Tidak menutup kemungkinan bahwa sertifikat pendidik itu nantinya hanya bersifat legalitas guna mendapatkan tunjangan profesi bagi guru dan dosen.
Lebih lanjut dalam Pasal 10 disebutkan bahwa kompetensi yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Berdasarkan bunyi Pasal 10 ini memunculkan suatu pertanyaan bahwa apakah lulusan LPTK itu tidak mempunyai kompetensi pedagogik, sehingga harus diperoleh lagi lewat pendidikan profesi? Lalu pendidikan profesi yang dimaksud seperti apa modelnya, apa isi/materi pendidikannya dan ilmu macam apa yang diperoleh dari pendidikan itu?. Apakah masih pantas seorang guru besar (Profesor) misalnya, dengan kualifikasi pendidikan doktor (S3) dan sudah memiliki masa kerja 20 tahun masih harus mengikuti pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik guna mendapatkan pengakuan sebagai tenaga profesional sesuai dengan bunyi Pasal 3.
Oleh karena itu, pendidikan profesi sebaiknya ditujukan kepada lulusan non LPTK yang ingin menjadi guru atau dosen, atau kepada guru atau dosen yang bukan lulusan LPTK dan belum memiliki ijazah akta IV. Tentu langkah ini jauh lebih baik dilakukan, apabila pendidikan profesi itu memang dianggap sebagai penyempurnaan kompetensi guru dan dosen, bukan hanya ditujukan untuk memberi sertifikat pendidik kepada guru dan dosen sebagai prasyarat memperoleh tunjangan profesi. Apalagi dijadikan sebagai wahana mencari proyek baru yang beban pembiayaannya dicarikan melalui APBN atau APBD di masing-masing daerah. Adanya kegiatan para pejabat LPTK yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara program sertifikasi untuk melalukan pertemuan (lobi) dengan pejabat PEMDA di beberapa daerah baru-baru ini, telah memunculkan anggapan bahwa rencana program sertifikasi itu lebih bersifat proyek ketimbang mempertimbangkan aspek urgensi, substansi, dan implementasinya
Dengan demikian, apabila pemerintah berkeinginan memberikan tunjangan profesi kepada guru dan dosen, maka persyaratannya bukan pada sertifikat pendidik, tetapi persyaratannya sebaiknya dalam bentuk lain, misalnya dengan memperhitungkan : (1) Kualifikasi Pendidikan, (2) Masa Kerja, dan (3) Jenjang Kepangkatan/Golongan atau Jabatan akademik. Sehingga Pasal 16 sebaiknya direvisi menjadi : Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki : (1) Kualifikasi pendidikan minimal diploma empat, (2) Masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun, dan (3) Memiliki kepangkatan minimal Pengatur/Golongan ruang III/c atau Guru ahli. Untuk dosen : (1) kualifikasi pendidikan minimal S2, (2) pengalaman kerja minimal 5 tahun, dan (3) memiliki kepangkatan minimal Penata/Golongan ruang III/c atau Asisten ahli.
Dengan memperhitungkan ketiga persyaratan tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan tunjangan profesi kepada guru dan dosen. Ini akan lebih realistis dan tindakan yang lebih adil daripada harus memperoleh sertifikat pendidik model baru tersebut. Apabila hal ini dilakukan berarti guru dan dosen mendapatkan tunjangan profesi atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan pengalaman kerja dan kualifikasi pendidikannya, dan hal itu tentu mengalami proses yang harus ditempuh oleh seorang guru atau dosen sebagai wujud nyata dari pengabdian yang dilakukannya dalam jabatan/profesinya.
Oleh karena itu, apabila pemerintah memang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, maka implementasi undang-undang guru dan dosen sudah seharusnya segera dilaksanakan, dan tidak perlu lagi harus menunggu program sertifikasi. Sebab program tersebut kemungkinan lebih banyak biasnya (merugikan keuangan negara) daripada manfaatnya kepada guru dan dosen. Pengalaman telah menunjukkan bahwa program Tes Kompetensi bagi guru yang telah dilakukan sejak tahun 2000 hingga 2003 hasilnya tidak banyak memberikan manfaat dan informasi yang berguna, bahkan tindak lanjut dari hasil tes kompetensi itu kurang mendapat perhatian. Guru yang telah dinyatakan kompeten maupun yang belum kompeten (berdasarkan hasil tes kompetensi) semuanya sama, yaitu mereka kembali mengajar seperti biasa, dan tidak pernah ada usaha tindak lanjut yang lebih nyata diberikan kepada guru yang dinyatakan tidak lulus atau belum kompeten itu. Ini berarti bahwa program Tes Kompetensi bagi guru hanya menghabiskan uang negara yang jumlahnya miliyaran bahkan triliyunan rupiah.
Disamping itu, adalah sungguh tidak layak jika kompetensi guru dan dosen diukur lewat tes kompetensi yang sifatnya hanya mengukur kemampuan kognitif. Kompetensi guru dan dosen tidak bisa diukur hanya lewat pemberian soal-soal kemudian dijawab dan diskor lalu diambil kesimpulan kompeten atau tidak kompeten. Kompetensi guru dan dosen bersifat holistik, menyeluruh dan meliputi banyak dimensi. Mulai dari aspek kognitif (penguasaan materi pelajaran), afektif, psikomotor, kemampuan mengajar termasuk penguasaan metodologi pembelajaran dan asesmen, prestasi belajar siswa hingga out comes suatu jenjang pendidikan. Karena itu, apabila ingin mengukurnya tidak cukup hanya memberikan soal-soal pilihan ganda kemudian dijawab dan diskor lalu diperoleh kesimpulan. Tes kompetensi guru yang dilaksanakan dalam kurung waktu 2000 hingga 2003 nampaknya hanya mengukur aspek kognitif, dan tentu saja hal ini merupakan suatu kesalahan yang besar.
Sudah cukup banyak fakta yang menunjukkan bahwa pemberian in service training kepada guru dalam bentuk kegiatan pelatihan/penataran dalam waktu relatif singkat dan sifatnya demonstratif tidak cukup signifikan meningkatkan kinerja, kualitas maupun profesionalisme guru. Banyak guru setelah mengikuti kegiatan pelatihan/penataran kemudian kembali ke sekolah tidak bisa berbuat banyak, bahkan mereka kembali mengajar seperti biasa tanpa adanya usaha inovatif dan kreatif untuk mengaplikasikan ilmu atau pengetahuan yang diperolehnya dari kegiatan pelatihan/penataran. Mengapa demikian, berbagai alasan klasik sering mereka kemukakan di antaranya di sekolah tidak tersedia sarana dan prasarana pendukung, biaya tidak ada, jumlah murid terlalu banyak dan sebagainya.
Karena itu, sudah saatnya pemerintah (Depdiknas) merubah model-model peningkatan kualitas/kompetensi/profesionalisme bagi guru lewat penataran/pelatihan yang sifatnya demonstratif dan selalu menggunakan metode prediksi dan estimasi. Usaha peningkatan kinerja/kompetensi guru harus diarahkan kepada program yang lebih realistis, salah satunya adalah meningkatkan gaji atau kesejahteraannya. Walaupun ratusan kali seorang guru mengikuti penataran/pelatihan, kinerja guru tidak akan optimal apabila kesejahteraannya (gaji) masih sangat minim. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja guru dan dosen untuk mengajar yang terbaik adalah dengan cara memberikan gaji yang layak. Kemudian setelah hal itu terpenuhi baru dilakukan tindakan pengawasan dan penegakan disiplin yang ketat, agar guru tidak lagi dijumpai berkeliaran kesana-sini pada waktu jam mengajar di sekolah dengan alasan untuk mencari tambahan penghasilan karena gaji yang diterimanya sangat minim. Demikian pula kepada para dosen, tidak perlu lagi harus hadir dimana-mana memberi kuliah di perguruan tinggi lain hanya dengan alasan menambah penghasilan.
Sebagai uraian penutup, ada beberapa hal yang disarankan: Pertama, pemerintah hendaknya segera mengimplementasikan undang-undang guru dan dosen dengan segera memberikan tunjangan profesi kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan dengan memperhatikan : (1) Kualifikasi pendidikan, (2) Masa kerja, dan (3) Kepangkatam/Golongan atau Jabatan akademik, tidak perlu menggunakan persyaratan sertifikat pendidik. Dalam rangka itu pula, sebaiknya ditinjau kembali tentang pemberian standar gaji pokok bagi guru dan dosen. Selama ini, besarnya standar gaji pokok yang diberlakukan tidak memperhitungkan perbedaan kualifikasi pendidikan (S1,S2,S3). Besarnya gaji pokok yang diterima oleh guru atau dosen yang berpendidikan S1 sama dengan gaji pokok yang berpendidikan S2 atau S3. Perbedaannya hanya terletak pada masa kerja yang diperoleh melalui kenaikan gaji berkala. Akibatnya, banyak dosen setelah menyelesaikan pendidikan S2 apalagi S3 lebih banyak mencari pekerjaan tambahan diluar tugas pokoknya. Bahkan seringkali tugas pokoknya, yakni mengajar pada institusinya bukan lagi menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi undang-undang guru dan dosen sebaiknya dilengkapi standar pemberian gaji pokok dengan memperhitungkan kualifikasi pendidikan tersebut. Sehingga ada perbedaan nyata antara besarnya gaji pokok guru atau dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3. Adalah sungguh tidak adil dan bijaksana kalau besarnya standar gaji pokok guru dan dosen yang berkualifikasi pendidikan S1 disamakan dengan yang berpendidikan S2 apalagi S3.
Kedua, dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan profesi bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal diploma empat, pemerintah hendaknya segera membuat program peningkatan kualifikasi guru. Hal ini harus segera dilakukan agar guru yang belum memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan itu tidak asal mengikuti pendidikan pada salah satu perguruan tinggi dengan tujuan hanya sekedar memperoleh gelar diploma empat atau sarjana (S1), tanpa memperhatikan jurusan yang dipilih apakah sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. Kalau hal ini terjadi, maka peningkatan kualifikasi akademik bagi guru nantinya tidak meningkatkan kualitas/kompetensinya. Dengan kata lain hanya bersifat formalitas.
Ketiga, apabila pendidikan profesi memang sangat diperlukan, maka pendidikan profesi itu sebaiknya direncanakan dan dirancang terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya mulai dari kurikulumnya sampai pada teknis pelaksanaannya, agar pelaksanaannya tidak terkesan terburu-buru yang berakibat kehilangan urgensi dan subtansinya. Disamping itu, agar isi/materi kependidikan yang ada pada kurikulum LPTK tidak tumpang tindih dengan materi/isi kurikulum pendidikan profesi tersebut. Demikian pula program pendidikan profesi yang dimaksud, hanya ditujukan kepada lulusan non LPTK yang berminat menjadi guru atau dosen ataukah yang sudah menjadi guru atau dosen dengan latar belakang pendidikan non LPTK dan belum memiliki ijazah akta IV. Kalau hal ini dilakukan berarti biaya pelaksanaan pendidikan profesi tidak lagi dibebankan kepada pemerintah, dan pelaksanaannya juga tidak bersifat instan. Tentu saja harus ada batasan yang jelas tentang kedudukan dan fungsi serta perbedaan nyata antara sertifikat pendidik dengan ijazah akta yang dikeluarkan oleh LPTK. Dengan demikian kedepan dalam rangka penerimaan calon guru baru khususnya CPNS, seorang calon harus memiliki : (1) Ijazah sarjana (S1), (2) Sertifikat pendidik (bagi lulusan non LPTK), dan (3) Ijazah akta IV.
Keempat, pemerintah perlu meninjau kembali undang-undang guru dan dosen khususnya Pasal 2(2), Pasal 3(2), Pasal10, Pasal 16 (1), Pasal 47(1c) dan Pasal 53(1), agar isi undang-undang tersebut tidak menimbulkan masalah baru yang memberatkan bagi guru dan dosen. Tanpa adanya revisi pada pasal-pasal tersebut akan menimbulkan kesan bahwa kehadiran undang-undang tersebut hanya sebagai ajang memunculkan ide proyek baru, bukannya meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.
Kamis, 05 Maret 2009
Sertifikasi Guru dan Dosen : Suatu Harapan atau Pelecehan
Diposting oleh erien gmelina putrindi di 01.46
Label: manajemen tenaga pendidikan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)









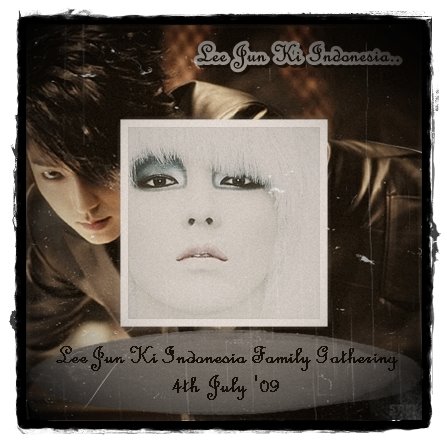






0 komentar:
Posting Komentar