Saya saat ini masih dalam frame 'miris'. Pengalaman mengejutkan tentang perilaku guru pada siswanya sampai sekarang belum sebaik yang saya baca di blog Sekolah Alam, cerita-cerita di buku, dan diskusi dengan kawan-kawan di tempat kuliah atau di lembaga pendidikan unformal. Pernah, dalam hitungan 1 semester, dua kali saya meneteskan air mata di depan siswa saya sekelas. Pasalnya, mereka gaduh ketika melakukan wawancara. Salah saya juga, saya tidak memantau. Akibatnya seorang guru yang merasa terganggu dengan suara dari luar kelas itu, mendatangi saya di kelas dan bertanya di depan pintu dengan galaknya, "Pelajaran apa sih sekarang?" Sungguh sadar, itu bukan salah anak-anak. Salah guru yang lupa, bahwa mereka hanyalah anak-anak yang memang harus selalu diingatkan. Tapi, amarah dan kecewa saya meluap sehingga menjadi tangis dan tentu saja tangis itu diterjemahkan anak-anak sebagai bentuk kesalahan terbesar mereka. Dan selanjutnya, dan selanjutnya.
Pertentangan antara pendidikan yang membebaskan dengan muatan-muatan titipan dan pesanan-pesanan masa depan membuat saya sering frustasi. Siapa yang mendukung saya? Siapa yang tidak setuju dengan sikap kepala sekolah yang kelewatan kasar, menendang tubuh siswa ketika gaduh sewaktu upacara akan dimulai? Siapa yang mendukung saya, untuk mengurangi beban hidup mereka, "Tidak ada PR, anak-anak!" Siapa yang bisa kompak menentang hukuman berdiri di depan kelas selama jam pelajaran dan lari mengitari lapangan jika tidak mengumpulkan tugas? Siapa yang bisa diajak bertukar pikiran tentang sekolah yang kembali ke zaman Flinstone? Di sekolah tempat saya mengajar tidak saya temukan siapa-siapa. Akibatnya, saya sangat tidak menikmati hari-hari mengajar. Datang ketika jamnya dan segera pulang jika jam mengajar berakhir.
Jika di Sekolahku Cintaku ada PTTN, saya ingin ada juga pembebasan terhadap dogma jati diri guru, tentu saja selain arahan-arahan untuk membebaskan diri dari belenggu penjara sekolah-bukankah pengekangan sama dengan penjara? Dulu guru harus bersanggul-berkebaya, untuk yang perempuan. Sekarang? Baju safari, sepatu fantopel, tas kerja seperti menjadi atribut wajib bagi seorang guru. Image building, mungkin. Padahal.saya akan bebas berekspresi dengan pakaian sporty. Saya rasa tak masalah makan siang bareng anak-anak, kumpul dengan mereka dan mengomentari kisah seru remaja. Tak salah saya menggunakan ransel, karena di dalamnya saya bisa bawa banyak buku cerita dan benda-benda aneh untuk mereka amati. Bukankah seperti itulah seharusnya seorang guru. Apa bedanya kita dengan mereka? Sadar atau tidak, kita sering berganti posisi dengan siswa/i itu. Mereka mengajarkan banyak hal. Mereka guru dan kita murid. Tentu akan sulit bagi kita untuk mempelajari mereka dengan utuh jika terjadi dikotomi. Bukankah kita adalah kawan yang membuat mereka merasa nyaman untuk bertanya dan menjawab banyak hal dengan gaya mereka sendiri?
Sering saya berpikir, apa saya tidak dewasa? Pertanyaan ini timbul akibat tidak percaya diri terhadap cita-cita yang sengaja digantungkan setinggi langit. Haha.sekarang saya jadi tertawa sendiri. Setelah membaca buku Poile Sangupta, baru sadar. Ternyata, menjadi dewasa sering kali menjadi kejam terhadap diri sendiri dan jika kita seorang guru atau (calon) orang tua, maka kita sudah sangat kejam terhadap masa depan siswa dan (calon) anak-anak kita. Iya, kan? Orang-orang yang memformat kedewasaan seringkali malah mengabaikan hal-hal kecil dan mulia untuk dilakukan, seperti tersenyum kepada orang lain yang berlaku kocak, bertanya tentang banyak hal yang mengherankan, ikut menyumbangkan saran terhadap pemecahan masalah orang lain tanpa tendensi, dan perilaku-perilaku lain yang tulus dan spontan.
Jadi, kesimpulan saya, menjadi dewasa seharusnya menjadi lebih mengerti tentang dunia dan tidak begitu saja terpengaruh terhadap sederetan tuntutan yang sering kali tidak manusiawi. "Hei, itu! Ya, yang di sana. Kamu tertawa terus dari tadi. Apa yang lucu? Coba, konsen sedikit lah!" Ini teguran keras saya pada siswa yang bercanda ketika pelajaran dimulai.(maklumlah, lagi frustasi) Padahal, mereka kan anak-anak. Kelak mereka akan selalu konsentrasi saat konsentrasi pada pelajaran memang benar-benar dirasakan manfaatnya. Sedangkan kini? Sekolah? Ah, beraaaat! Konsentrasi? Susaaaah! Jadi pintar? Jauuuuh!
Teman, mencoba menyelaraskan antara pemenuhan terhadap muatan kurikulum yang demikian padat dengan ide-ide ini saya dan kawan-kawan di SINERGI mulai membuka Bimbel. Siswanya adalah siswa-siswa saya selama di SD. Ortu percaya saya bisa membuat mereka merasa, bahwa belajar itu menyenangkan. Akhirnya, mereka dikirim ke rumah saya untuk Bimbel. Satu cerita yang membuat saya jadi makin prihatin. Siswa di Bimbel kami hanya 3 orang. Salah satunya tidak mau digabung dengan yang lain. Nama anak lucu dan menggemaskan itu Aditya. Hampir tiap datang, salah satu bab pada buku PR terbitan Epsilon sudah selesai dikerjakan. Adit datang dengan cengirannya yang khas. Saya merasa Adit yang mempunyai sejarah lima sebanyak 5 mata pelajaran dan terancam tinggal kelas ini sudah mulai ada peningkatan. Tapi, suatu hari Bunda Adit telepon sambil menahan tangis. Beliau mengadukan Adit tidak mengerjakan PR tiga kali dan tugas di kelas tidak selesai juga. Padahal, sekolah baru efektif-setelah liburan semester, selama kurang dari satu bulan. "Bisa-bisa dia tidak naik, Bu!" Sebuah vonis yang menakutkan baik bagi siswa, orang tua, dan guru.
Saya gemas. Ingin rasanya kusulap sebuah sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak. Sebuah sekolah yang semua programnya disambut dengan ceria dan mereka berlomba-lomba untuk mengajak orang-orang di sekitarnya dengan bahagia untuk mendengarkan pengalaman bersekolah. Mereka akan bercerita tentang petualangan bersama gurunya, tentang pemberian sumbangan, tentang penghargaan terhadap karya, tentang perencanaan kegiatan belajar, tentang diskusi di pinggir sungai kecil, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka hidup. Mereka tak takut dengan masa depan dan kedewasaan.
Insyaallah ini bukan sekadar mimpi. Kelak, anak-anak di banyak tempat akan bersorak, "Ayooo seeekooolaaah!!!"
Kamis, 05 Maret 2009
Sebuah Penjara Bernama Sekolah
Diposting oleh erien gmelina putrindi di 01.27
Label: manajemen kesiswaan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)









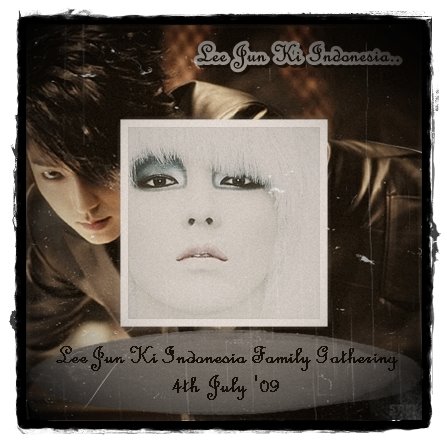






0 komentar:
Posting Komentar