Oleh M. Khoirul Muqtafa
Paradigma multikultural yang marak didengungkan sebagai langkah alternatif dalam rangka mengelola masyarakat multikultur sebagaimana Indonesia tampaknya masih menjadi wacana belaka. Gagasan genuine ini belum mampu diejawantahkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, dalam tindakan praksis. Apa yang mengemuka sepanjang tahun 2003 kemarin merupakan indikasi nyata ikhwal di atas. Sebagai tamsil yakni fenomena (di)muncul(kan)nya UU ”kontroversi” Sisdiknas yang sengaja didesakkan ”kelompok mayoritas”.
Masih munculnya keinginan sekelompok orang supaya hukum-hukum yang bersumber dari agama yang dipeluknya dilegalisasi masuk ke dalam KUHP tanpa proses objektifikasi. Kasus RUU Kerukunan Beragama yang sangat kental dengan aroma intervensi negara yang deterministik dalam kehidupan umat beragama juga menandai betapa lemahnya nalar multikultural dalam benak bangsa ini.
Perihal di atas sungguh memprihatinkan ketika kita menilik kembali latar sosiologisantropologis bangsa ini. Indonesia adalah masyarakat majemuk, baik secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal berbagai kelompok masyarakat yang kini dikategorikan sebagai ”Bangsa Indonesia” dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai suku bangsa, kelompok penutur bahasa tertentu, maupun ke dalam golongan penganut ajaran agama yang berbeda satu dengan lainnya. Sedang, secara vertikal berbagai kelompok masyarakat itu dapat dibeda-bedakan atas dasar mode of production yang bermuara pada perbedaan daya adaptasinya.
Dalam realitas-empirik, kenyataan ini justru kerap di(ter)abaikan. Yang terjadi seringkali bukannya penghargaan dan pengakuan atas kehadiran yang lain akan tetapi upaya untuk ”mempersamakan” (conformity) atas nama persatuan dan kesatuan. Politik sentralisme kekuasaan yang pada masa Orde Baru memaksakan "monokulturalisme" yang nyaris seragam adalah bukti nyata hal di atas. Tak aneh, kalau kemudian monokulturalisme ini memunculkan reaksi balik, yang mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan gejala "provinsialisme" yang hampir tumpang tindih dengan "etnisitas".
Politik identitas kelompok, seiring dengan menggejalanya komunalisme, makin menguat. Konflik antarsuku maupun agama muncul bak cendawan di musim hujan. Kesatuan dan persatuan yang diidam-idamkan selama ini ternyata semu belaka. Yang mengemuka kemudian adalah kepentingan antarsuku, daerah, ras ataupun agama dengan mengenyampingkan realitas atau kepentingan yang lain. Bahkan tak jarang, suatu kelompok menghalalkan segala cara demi mewujudkan kepentingan ini.
Faktor lain yang turut menyebabkan mandulnya pendidikan multikultural pada tingkat praksis bisa jadi disebabkan masih dominannya wacana ”toleransi” dalam menyikapi realitas multikultural tersebut. Toleransi hanya mungkin terjadi apabila orang rela merelativisasi klaim-kalimnya sebagaimana diungkap oleh Richard Rorty, seorang filsuf neo-pragmatis. Penghargaan atas yang lain sebagaimana dibayangkan dalam ”toleransi” memang dibutuhkan. Namun, toleransi seringkali terjebak pada ego-sentrisme. Ego-sentrisme di sini adalah sikap saya mentoleransi yang lain demi saya sendiri. Artinya, setiap perbedaan mengakui perbedaan lain demi menguatkan dan mengawetkan perbedaannya sendiri (I am what I am not). Yang terjadi kemudian adalah ko-eksistensi bukannya pro-eksistensi yang menuntut kreativitas dari tiap individu yang berbeda untuk merenda dan merajut tali-temali kebersamaan. Tak aneh kalau kemudian yang muncul bukannya situasi rukun malah situasi acuh tak acuh (indifference).
Pendidikan Multikultural
Sampai di sini, layak kita meneguhkan kembali paradigma multikultural tersebut. Peneguhan ini harus lebih ditekankan kepada persoalan kompetensi kebudayaan sehingga tidak hanya berkutat pada aspek kognitif melainkan beranjak kepada aspek psikomotorik. Peneguhan ini bermaksud mendedahkan kesadaran bahwa multikulturalisme, sebagaimana diungkap oleh Goodenough (1976) adalah pengalaman normal manusia. Ia ada dan hadir dalam realitas empirik. Untuk itu, pengelolaan masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dilakukan secara taken for granted atau trial and error. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated, dan berkesinambungan. Di sinilah fungsi strategis pendidikan multikultural sebagai sebuah proses di mana seseorang mengembangkan kompetensi dalam beberapa sistem standar untuk mempersepsi, mengevaluasi, meyakini, dan melakukan tindakan.
Beberapa hal yang dibidik dalam pendidikan multikultural ini adalah: pertama, pendidikan multikultural menolak pandangan yang menyamakan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan juga bermaksud membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer dalam mengembangkan kompetensi kebudayaan semata-mata berada di tangan mereka melainkan tanggung jawab semua pihak.
Kedua, pendidikan ini juga menolak pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Hal ini dikarenakan seringnya para pendidik, secara tradisional, mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient. Oleh karena individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam berbagai dialek atau bahasa, dan berbagai pemahaman mengenai situasi-situasi di mana setiap pemahaman tersebut sesuai, maka individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam sejumlah kebudayaan. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural akan melenyapkan kecenderungan memandang individu secara stereotip menurut identitas etnik mereka. Malah akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak-didik dari berbagai kelompok etnik.
Ketiga, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi seseorang pada suatu waktu ditentukan oleh situasinya. Meski jelas berkaitan, harus dibedakan secara konseptual antara identitas-identitas yang disandang individu dan identitas sosial primer dalam kelompok etnik tertentu.
Keempat, kemungkinan bahwa pendidikan meningkatkan kesadaran mengenai kompetensi dalam beberapa kebudayaan akan menjauhkan kita dari konsep dwi-budaya (bicultural) atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Karena dikotomi semacam ini bersifat membatasi kebebasan individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan.
Dalam melaksanakan pendidikan multikultural ini mesti dikembangkan prinsip solidaritas. Yakni kesiapan untuk berjuang dan bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain dan bukan demi dirinya sendiri. Solidaritas menuntut untuk melupakan upaya-upaya penguatan identitas melainkan berjuang demi dan bersama yang lain. Dengan berlaku demikian, kehidupan multikultural yang dilandasi kesadaran akan eksistensi diri tanpa merendahkan yang lain diharapkan segera terwujud.
Penulis adalah Koordinator Piramida Circle Jakarta.
Selasa, 02 Juni 2009
Paradigma Multikultural
Langganan:
Posting Komentar (Atom)









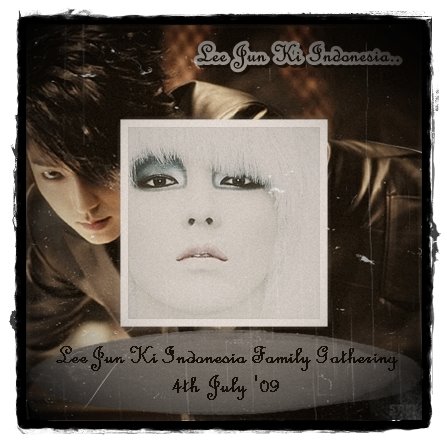






0 komentar:
Posting Komentar